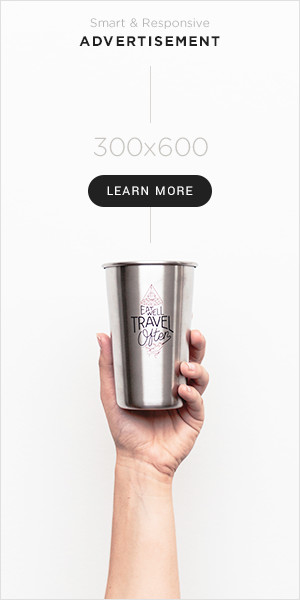Oleh: Soni Samoe, Pendiri LSM LABRAK (Lembaga Aksi Bela Rakyat)
KONTRADIKSI.ID Pohuwato, 16 Agustus 2025 –Delapan puluh tahun lalu, Indonesia lahir dari pergulatan sejarah, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan dideklarasikan sebagai penanda berakhirnya kolonialisme yang selama berabad-abad menindas. Namun, setelah delapan dekade, pertanyaan mendasar muncul: apakah rakyat benar-benar merdeka di tanahnya sendiri, ataukah kemerdekaan itu hanya berganti kulit?
Di Pohuwato, Gorontalo, jawaban atas pertanyaan itu pahit untuk ditelan. Wilayah kaya emas ini menjadi contoh telanjang bagaimana hegemoni modal dapat mengalahkan kedaulatan rakyat. Perusahaan tambang raksasa hadir dengan bendera legalitas, tetapi meninggalkan jejak penyingkiran terhadap penambang rakyat yang telah lama bergantung pada tanah ini untuk hidup.
Pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi perisai rakyat, justru tampak lemah di hadapan kekuatan korporasi. Janji menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah resmi ditetapkan, tak kunjung direalisasikan. Di sisi lain, perusahaan beroperasi leluasa tanpa hambatan berarti.
Tragedi 21 September 2023 adalah titik kulminasi kemarahan. Kantor Bupati Pohuwato dibakar massa bukan karena rakyat anti-pemerintah secara membabi buta, tetapi karena frustrasi mendalam terhadap kebijakan yang dianggap memihak korporasi, mengabaikan hak-hak warga, dan membiarkan ketidakadilan berulang.
Aksi itu dipicu oleh kegagalan pemerintah menyelesaikan tuntutan ganti rugi lahan terhadap perusahaan Pani Gold. Rakyat yang selama ini hidup dari hasil tambang dipaksa melihat tanah mereka diklaim sebagai konsesi perusahaan. Seolah-olah sejarah mereka dihapus hanya dengan selembar dokumen izin.
Fenomena ini adalah wajah baru kolonialisme—corporate colonialism. Penjajahan tak lagi berbentuk pasukan bersenjata yang menguasai tanah, tetapi dalam rupa surat kontrak, izin tambang, dan retorika investasi. Bedanya, kali ini “penjajah” datang dengan restu negara.
Pemerintah sering kali berdalih bahwa investasi tambang membawa pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan itu semu jika hanya menguntungkan segelintir elite politik dan pemilik modal, sementara penambang rakyat dan masyarakat lokal justru terdorong ke pinggir jurang kemiskinan.
Data lapangan menunjukkan mayoritas tenaga kerja di lingkar tambang justru didominasi pendatang, sementara warga lokal kehilangan akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang keluarga mereka. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga pengingkaran terhadap hak-hak sosial dan budaya.
Dalam konteks 80 tahun kemerdekaan, ironi ini semakin mencolok. Para pejuang kemerdekaan dulu berkorban demi mengusir penjajah yang merampas tanah dan sumber daya. Kini, rakyat harus berhadapan dengan perusahaan yang melakukan hal serupa, hanya dengan bahasa dan metode yang lebih “modern” dan “legal”.
Situasi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang cenderung kosmetik—sekadar menenangkan amarah publik, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Keberanian politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat tampak absen, tergantikan oleh diplomasi transaksional dengan pemilik modal.
Setiap tahun, upacara 17 Agustus diadakan dengan penuh khidmat. Bendera Merah Putih dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan pidato kemerdekaan dibacakan. Namun, bagi sebagian rakyat Pohuwato, semua itu terasa seperti ritual simbolik yang tidak mengubah kenyataan bahwa mereka masih “terjajah” di tanah leluhur mereka.
Kedaulatan sejati tidak cukup hanya tercatat di konstitusi, tetapi harus hadir dalam kebijakan konkret yang melindungi hak rakyat. Tanpa itu, kemerdekaan akan menjadi mitos yang terus diulang tanpa makna substansial.
Konflik agraria dan pertambangan di Pohuwato adalah alarm bagi seluruh bangsa. Ini menandakan bahwa struktur kekuasaan dan kebijakan ekonomi kita masih memberi ruang besar bagi eksploitasi yang mengorbankan rakyat kecil.
Narasi pembangunan yang mengagungkan investasi tanpa memikirkan distribusi manfaat adalah bentuk lain dari ketidakadilan. Rakyat hanya dilibatkan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki hak menentukan masa depan tanah mereka.
Dalam kasus Pohuwato, ketimpangan ini semakin nyata ketika perusahaan memonopoli wilayah tambang, sementara penambang tradisional dikriminalisasi karena dianggap melanggar hukum. Padahal, mereka hanya mempertahankan hak untuk hidup dari tanah yang sudah mereka kelola turun-temurun.
Negara yang merdeka seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemilik sah sumber daya alam, bukan hanya sebagai penonton dari jarak jauh. Setiap kebijakan harus lahir dari keberpihakan kepada kepentingan publik, bukan dari lobi-lobi meja perundingan yang didominasi oleh korporasi.
Dalam refleksi ini, penting diingat bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari sistem ekonomi-politik yang menindas. Rakyat berhak atas kedaulatan tanah, air, dan udara—bukan hanya secara simbolik, tetapi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tanpa perubahan fundamental dalam cara negara mengelola sumber daya, konflik seperti di Pohuwato akan terus berulang. Rakyat akan terus menjadi korban, sementara keuntungan besar mengalir keluar dari daerah tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan lokal.
Delapan puluh tahun kemerdekaan harusnya menjadi momentum untuk membalik keadaan: mengembalikan hak rakyat atas tanahnya, memperkuat posisi pertambangan rakyat lokal, dan memastikan bahwa setiap kebijakan tambang berbasis pada prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Jika negara gagal mewujudkan hal ini, maka kemerdekaan hanya akan menjadi slogan kosong—bendera akan tetap berkibar setiap tahun, tetapi di bawahnya, rakyat terus menunduk, memikul beban ketidakadilan yang diwariskan dari masa ke masa, dengan wajah penjajahan yang kini terselubung di balik nama pembangunan.
Redaksi-TIMKontradiksi.ID